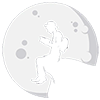Kesulitan Saat Melakukan Tari Piring: Cari Tahu Disini!

Tari Piring menjadi salah satu tarian daerah yang berasal dari Minangkabau, Sumatra Barat. Piring yang menjadi properti dalam tari ini sering kali menjadi kesulitan saat melakukan tari Piring. Mengingat gerakan tariannya yang lincah, serta berpindah ke sana ke mari dengan cepat.
Meski begitu, hingga saat ini tarian Piring masih terus menjadi primadona suku Minangkabau. Bahkan dalam acara besar, seperti pernikahan dan perayaan lainnya, tari Piring menjadi tarian untuk menyambut tamu undangan. Tak heran jika tari Piring tetap eksis di masa modern saat ini.
Gerakan Pada Tari Piring
Gerakan pola lantai tari Piring umumnya dikemas dengan gabungan berbagai pola tari. Pola yang biasanya dipakai dalam tari ini adalah lingkaran kecil, lalu besar, serta sebaliknya. Hal ini bisa juga menjadi kesulitan saat melakukan tari Piring karena penari juga harus menyesuaikan tempo.
Penambahan piring sebagai properti ketika menari juga menjadi atraksi yang menegangkan, sehingga tidak bisa diremehkan begitu saja. Tak heran jika penari tari Piring harus berlatih dalam kurun waktu yang panjang agar dapat membawakan gerakan tari tersebut dengan baik dan benar.
Baca juga: Fakta Unik dan Menarik, Serta Pencipta Tari Piring
Menari Tari Piring? Sesulit Apa, ya?
Bagi kamu yang ingin mencoba belajar tari Sumatra Barat ini, berikut beberapa kesulitan saat melakukan tari Piring yang mungkin kamu jumpai.
1. Pemakaian Properti Piring
Sudah menjadi rahasia umum jika dalam tari Piring terdapat properti piring asli. Benda tersebut nantinya akan ditempatkan pada kedua telapak tangan sembari penari melakukan gerakan tari Piring. Hal ini bisa dibilang sulit karena penari perlu belajar keseimbangan agar tidak jatuh.
Adanya piring dalam tarian ini bukanlah tanpa alasan. Sebelum tarian Piring berakhir, piring tersebut akan menjadi media atraksi, dimana piring akan dijatuhkan ke area tengah tempat menari. Dan nantinya penari akan menari di atas pecahan piring mengikuti ketukan irama lagu.
2. Tempo Gerakan yang Cepat
Perlu kamu ketahui bahwa dalam tari Piring, tempo lagu berada pada titik pelan dan semakin lama semakin cepat. Menjaga keseimbangan agar piring tidak jatuh, ditambah gerakan tempo tarian yang begitu cepat tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi penari tari suku Minang ini.
Ketika musik mulai bergema penari akan mulai menari dengan pelan, namun seiring lagu berputar, maka makin lama, kecepatan lagu akan bertambah. Pada saat yang sama, penari harus tetap menjaga keseimbangan agar piring tidak terlepas atau tergelincir dari genggaman tangan.
3. Atraksi di Akhir Tarian
Bagi kamu yang baru pertama kali menonton tari Piring, mungkin akan terkejut menjelang tarian berakhir. Piring yang merupakan peran utama dalam tarian ini bukan hanya hiasan semata. Ketika pertunjukkan akan selesai, piring ini akan dibanting ke arah tengah area menari tarian ini.
Otomatis ketika piring dibuang ke tengah, benda tersebut akan pecah dan berserakan begitu saja. Tentu saja agar tidak terkena penonton, penari harus melempar piring dengan benar. Lalu kemudian para penari akan menari di atas pecahan piring yang terlempar. Sangat menegangkan!
Demikian kesulitan saat melakukan tari Piring yang tentunya hanya dapat dilakukan oleh ahli dan didampingi seorang Profesional. Atraksi terakhir memang cukup membuat takut, mengingat pecahan piring termasuk benda tajam dan dapat melukai telapak kaki penari tari Piring Minang.
Namun kamu tidak perlu khawatir, sebab ada trik dalam melakukan tarian Piring tersebut. Peringatan kembali bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan ahli, maka sangat dilarang keras untuk meniru atraksi ini, ya. Karena akan sangat berbahaya jika kamu memaksa melakukannya.